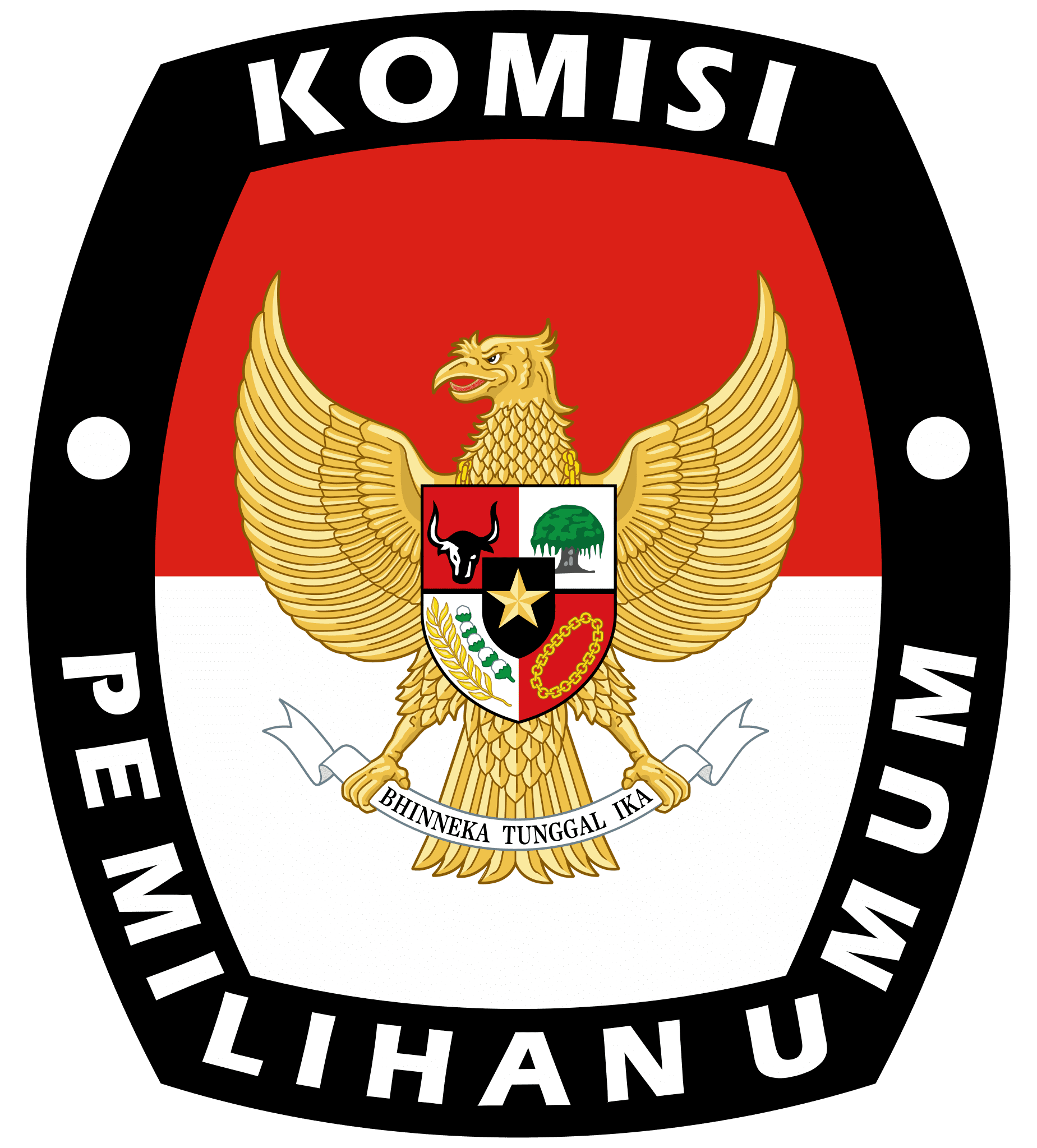Memahami Cara Berfikir Pemilih : Refleksi Atas Kelelahan Demokrasi
oleh : Latief Muhtar ( Kepala Sub Bagian Parhubmas dan SDM KPU Kota Tasikmalaya )
Setiap pemilu tiba, kita sering kali mendengar seruan: “Jangan golput!” Namun ketika partisipasi tetap rendah, terkadang kita tergesa gesa mengambil kesimpulan : rakyat apatis, tidak peduli, atau tidak menarik buat rakyat.
Padahal, mungkin bukan itu problemnya—bisa jadi kita keliru dalam cara memahaminya.
Neurosains modern mengungkap sebuah kaidah yang menyebutkan: manusia tidak bertindak karena tahu, tapi karena merasa. Seperti yang dikemukakan oleh ahli saraf dari Kanada Donald Calne, emosi adalah instrumen pendorong utama atas sebuah tindakan, sementara pada bagian lain, ada namanya logika. Logika ini cenderung hadir tidak bersamaan dengan emosi, ia hadir di belakang—sebagai alasan, bukan pemicu. Artinya, menyampaikan informasi tentang tanggal, lokasi, dan tata cara mencoblos—tanpa menyentuh emosi—sama seperti mengirim undangan ke pesta yang dianggap tak penting bagi tamunya.
Secara alamiah, Otak manusia didesain untuk bertahan hidup, bukan untuk memilih. Ia menghemat energi, menghindari risiko, dan mencari kepastian. Jika datang ke TPS dianggap merepotkan dan dalam benaknya ada anggapan nanti hasilnya meragukan, serta dampaknya tidak terasa, maka otak secara alami akan memilih jalan termudah, yaitu diam.
Inilah akar golput yang sering tidak disadari: bukan sikap politik, namun respons neurologi terhadap sistem yang terasa jauh, rumit, dan tak bermakna.
Yang kita perlukan kedepan, bukan sekedar kampanye anti-golput, tapi pendekatan pendidikan pemilih yang memahami cara kerja otak manusia.
terkadang, kita penyelenggara pemilu sering kali terjebak dalam logika “transfer informasi”. Sosialisasi terfokus pada prosedur: jam berapa, di mana, bagaimana mencoblos. Padahal, mengetahui tidak sama dengan peduli.
Sebagaimana yang dijelaskan oleh ahli saraf Antonio Damasio, pengambilan keputusan selalu melibatkan emosi. Tanpa sinyal emosional, otak kesulitan memilih—meski logikanya telah memahami. Seseorang datang ke TPS bukan karena ia tahu aturan, tapi karena ia merasa bahwa pilihannya akan mengubah hidupnya dan generasinya kedepan, akan mengubah harga gabah, biaya Kesehatan yang terjangkau, atau kualitas udara di kotanya. Pesan seperti “Setiap keputusan di bilik suara adalah doa untuk masa depan anakmu” bukan sekadar pesan biasa—ia menyentuh bagian otak yang mengatur motivasi dan keberlangsungan sosial.
Lebih jauh lagi, perilaku demokratis tidak lahir dari satu kali sosialisasi, tapi dari pengalaman berulang yang positif. Prinsip dasar dalam psikologi saraf menyatakan bahwa pengalaman yang diulang-ulang dan dikaitkan dengan perasaan positif akan membentuk suatu kebiasaan. Jika antrean di TPS panjang dan kacau, otak akan mengasosiasikan “memilih” dengan stres. Tapi jika pengalaman itu lancar, baik, dan dihargai, otak akan membentuk kebiasaan: mencoblos sama dengan tanggung jawab moral.
oleh karenanya kedepan, penyelenggara perlu menguatkan Kembali kapasitas institusionalnya, terutama tidak hanya mengurusi sebatas demokrasi prosedural, akan tetapi kedepan saatnya penyelenggara bertransformasi menjadi arsitek perilaku demokratis. Ini mengandung makna mengembangkan kapasitas baru—literasi neuropolitik, kemampuan bercerita, empati sosial, dan kolaborasi dengan seniman, akademisi, dan komunitas lokal. Model sosialisasi harus bergerak dari “Apa yang harus kamu lakukan” ke “Mengapa ini penting bagimu”.
Demokrasi yang sehat bukan hanya diukur dari angka partisipasi, namun dari seberapa besar partisipasi itu tertanam dalam kesadaran kolektif. rasanya tidak terlalu berlebihan jika memasang target untuk membuat warga merasa aneh jika tidak memilih—karena memilih bukan lagi tugas, tapi komunitas kewargaan.
Demokrasi membutuhkan dua hal sekaligus: kejelasan prosedur dan kedalaman. penyelenggara menyediakan yang pertama; partai sebagai peserta menghidupkan yang kedua. Namun jika keduanya berjalan sendiri-sendiri, partisipasi akan tetap rapuh—naik saat ada euforia, turun saat kepercayaan surut.
jika kita mau perumpamakan, kira kira metaforanya "penyelenggara menyediakan jalan yang mulus (the highway), sementara Partai Politik menyediakan alasan yang kuat (the destination) mengapa pemilih harus menggunakan jalan itu". Dengan begitu, pemilih akan secara sukarela berkorban mengeluarkan energi untuk mencoblos.
![]()
![]()
![]()